ORANG TUA TAK PUNYA WAKTU UNTUK LAGU…
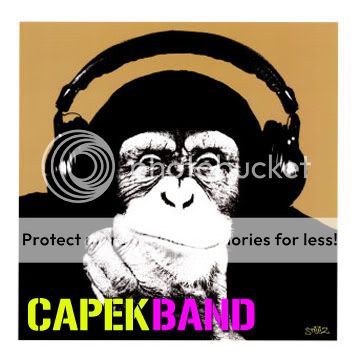
“Tambah tua malah nggak ada waktu buat nikmatin musik. Satu-satunya kesempatan pas nyetir. Itu aja lebih sering radio,” keluh seorang kawan. Di rumah dia harus berbagi dengan televisi. Di kamar tak mungkin memasang pemutar CD seperti anak-anaknya karena istrinya lebih menyukai televisi.
Menikmati musik yang dia maksudkan adalah mendengarkan musik yang dipilihnya sendiri. Bukan terpaksa mendengarkan musik yang diputar oleh orang lain.
Pakai headphone atau earphone? Tak semua orang dari generasi saya terbiasa dengan Walkman pada masa mudanya, dan setelah tua tak mampu membiasakan diri dengan portable digital music player.
Saya sendiri sejak dulu termasuk tak betah dengan headphone. Kuping cepat panas dan pegal. Saya lebih memilih menyetel musik (kadang juga dari radio) secara pelan, suaranya langsung dari kotak spiker sekadarnya, asal bunyi. Jika memungkinkan, dan lingkungan saya anggap menenggang, maka volume pun saya naikkan sedikit.
Keluhan bahwa makin tua makin sedikit waktu untuk menikmati musik tak hanya saya dengar dari seorang. Jangankan lagu baru, untuk lagu lama pun kurang waktu. Barangkali itulah sebabnya orang usia 40+, kalau ada waktu, cenderung memutar lagu lama. Selain bernostalgia (ini alami, Anda yang masih sangat belia pun akan mengalami hahaha) ya karena cuma itu yang dikenalnya.
Taruh kata pemukulrataan saya ini benar, paling hanya cocok untuk generasi saya. Generasi yang lebih muda, dan jauh lebih muda, mengalami terpaan dengaran yang jauh lebih kaya melalui peralatan pribadi. Akhirnya musik pribadi menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Kuping bisa diajak kompromi untuk bersaudara dengan headphone. Ketika usia bertambah mereka terbiasa menulikan diri secara bertahap dengan sumbat kuping bersuara….
Generasi saya, dan di atas saya, saat bocah mengalami hanya ada satu radio, satu turntable, dan satu cassette player untuk satu rumah. Alat hiburan adalah milik bersama –– mirip televisi pada umumnya keluarga sekarang.
Baru pada awal 80-an, seiring bertambahnya kemakmuran, maka satu kamar bisa memiliki radio dan cassette player sendiri. Setidaknya pada mahasiswa pemondok kemewahan kecil kelas menengah itu mulai terasa.
Saat itu cara murah untuk mendapatkan pemutar stereo adalah memanfaatkan cassette player bekas untuk mobil. Tinggal menambahkan adaptor dan spiker rakitan sendiri terciptalah musik pribadi –– bisa nonstop, auto-reverse pula. Itu lebih berbunyi ketimbang pemutar mono dengan spiker yang menyatu.
Di bawah kelas itu anak indekosan hanya punya radio transistor dua band (guyonnya: kalau lagi bokek, yang satu band digadaikan) yang bisa ditaruh di bibir sumur saat mencuci pakaian.
Masuknya mini-compo pada pertengahan 80-an, dimulai dari Sony, telah memperkaya cara menikmati musik secara pribadi. Bahwa kamar sebelah mengeluhkan kegaduhan stan pasar malam, ya silakan berkompromi.
Begitu seterusnya sehingga untuk penikmatan musik pribadi muncul komputer multimedia, ponsel, dan akhirnya iPod(-iPod-an). Lantas ke mana orang-orang tua?
Sebagian dari mereka bisa adaptif dengan earphone sambil memerhatikan sekeliling, bahkan diajak bicara pun merespon. Sebagian lainnya masih bergantung pada kotak spiker. Sialnya kalau di kantor tak memiliki ruang sendiri maka mereka akan mati angin. Meringkuk dalam kubus kerja, padahal hanya mengandalkan spiker bawaan komputer, berarti harus menenggang kuping tetangga agar tak tercipta stan pasar malam.
Ketika musik digital memurah, bajakannya ada di mana-mana (terutama untuk “musik demokratis” –– disukai banyak kuping), dan pemutarnya pun ada di mana-mana, ada saja yang merasa tak punya waktu untuk menikmati musik kecuali ketika menyetir sendirian.
Seorang kawan getun ketika menyadari bahwa dia hapal beberapa lagu baru akibat redundansi oleh televisi dan komputer sejawatnya. Katanya, “Cilaka bener, soalnya aku nggak suka lagu-lagu itu tapi otakku kadung kecuci!”
Memang cilaka. Jangan-jangan saya juga.
© Gambar asli praolah: unknown