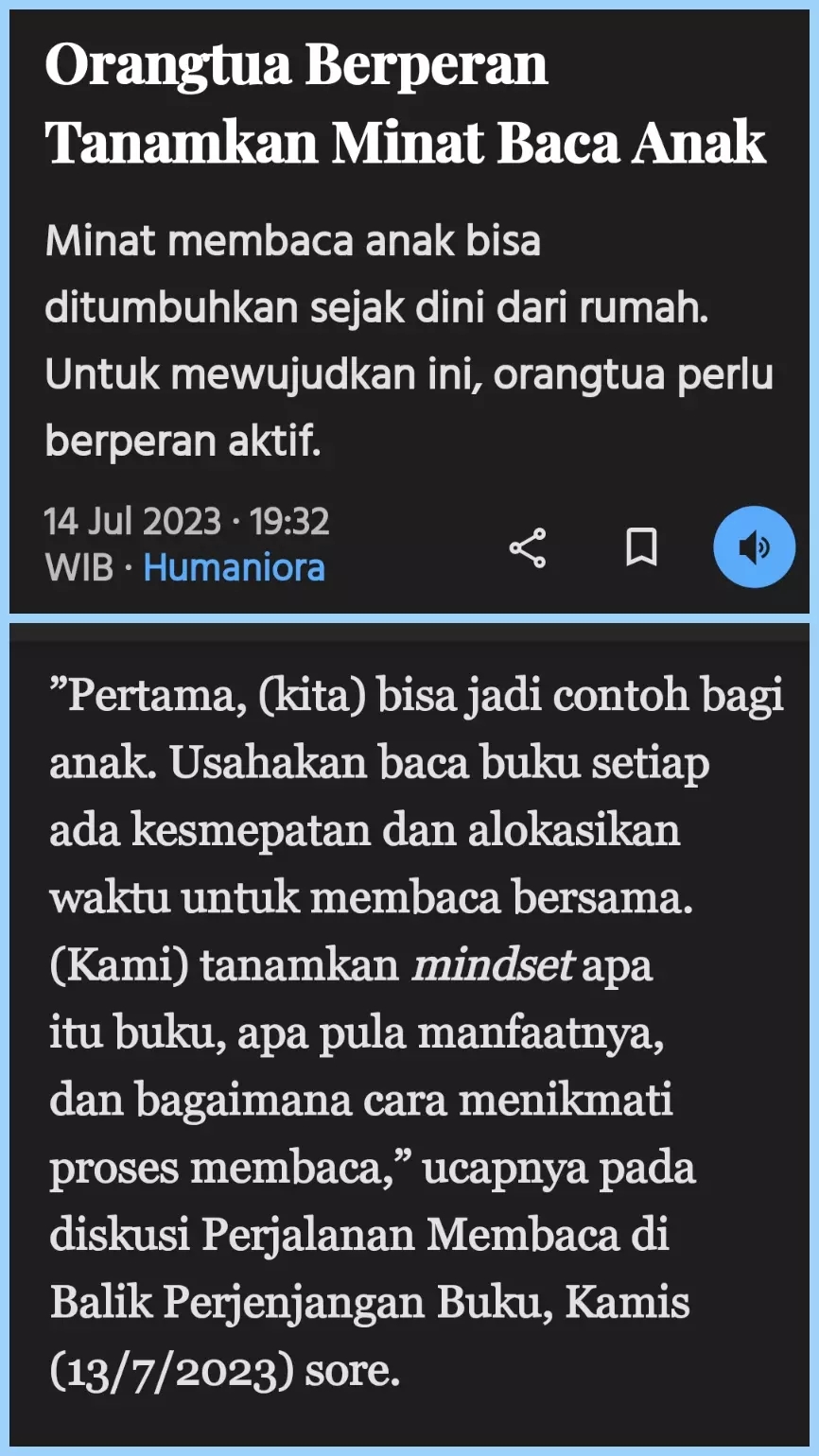
Saat membaca judul, dari Kompas.id, seperti tangkapan layar di atas, saya malas untuk membacanya. Rasanya kok bersua slogan klise semacam peran pemuda dalam pembangunan. Namun akhirnya saya baca juga. Begitu juga berita lain yang relevan, dari arsip, dalam tautan di tengah laman tersebut.
Dalam dua tangkapan layar, terutama yang empat kotak, isinya bisa membikin Anda bingung. Dalam gambar pertama tak jelas itu ucapan siapa. Apa boleh buat, namanya juga tangkapan layar. Seperti gambar serupa di WhatsApp, tanpa membaca sumber asli kita bisa salah tafsir, dan lebih celaka lagi jika tangkapan layar itu fiktif. Literasi kita seperti diejek.

Saya tak hendak membahas berita itu. Isinya juga cuma begitu. Saya malah merenungkan kenyataan sekarang: hidup kita bersama layar ponsel. Apapun terhubung ke internet. Misalnya pun anak banyak membaca dari ponsel — bukan cuma bermain gim dan menonton video — apakah hasilnya akan berbeda dari membaca kertas?
Biarlah para guru dan ahli pendidikan yang menjawab pertanyaan saya. Mereka lebih paham daripada saya. Lha wong sarjana semua, kan?
Persoalan lain, berapa banyak guru dari generasi boomers yang sarjana hingga generasi milenial, dan gelarnya dipasang, yang masih doyan buku kertas?
Pertanyaan saya tak membatasi bidang ajar para guru maupun tingkat sekolah yang diajar. Survei dapat menjawab hal itu, misalnya dalam seminggu membaca berapa halaman buku — semoga responden jujur.
Memang sih ada asumsi yang seolah tak adil: beban guru IPS dan bahasa tak seberat guru IPA dan matematika. Mungkin benar. Guru bahasa Indonesia saya di SMA, namanya Pak Hadi, saat itu yakin majalah Horison sudah mati, padahal saya yang bukan penyuka sastra punya edisi baru.
Guru lain, Pak Tjipto, mengajar kewarganegaraan, tak mau menjawab saat saya tanyakan anomali politik Indonesia saat itu: Golkar bukan partai, tapi ikut pemilu, dan punya kursi di parlemen, sementara militer punya kursi di DPR karena tak ikut pemilu, padahal harus terwakili. Pak Guru juga tak dapat menjelaskan kenapa amtenar wajib mencoblos Golkar.
Saya dulu sering kecewa terhadap guru. Di SMP ada guru olahraga dan pendidikan jasmani, namanya Pak Dar, yang gemar menghukum murid yang tak dapat menjawab pertanyaan. Tetapi ketika saya tanyakan hal seputar terjun payung, gantole, reli, dia bingung lalu berkelit itu bukan olahraga yang harus diketahui. Padahal hingga kini saya bukan penyimak berita olahraga.
Di SMA hal itu berulang. Guru sejenis, namanya Pak Widodo, juga tak mau tahu. Tetapi ketika lapangan basket sekolah difungsikan juga sebagai lapangan tenis sore hari, untuk guru, dia bersemangat membahas tenis dan bikin pertanyaan seputar itu.
Nah, kembali kepada minat dan kebisaan baca anak terhadap kertas, apakah gurunya suka baca, bahkan pada zaman keemasan media cetak?
Saya sih bukan kutu buku sejak kecil, hanya membaca sesuka saya dengan minat yang acak, tetapi tak ada beban karena saya bukan guru.

Tentu saya memahami kesenjangan di Indonesia yang rumit ini. Yang saya contohkan dalam pengalaman saya adalah guru di kota, meskipun dulu kotanya kecil, cuma satu kecamatan berisi sembilan kelurahan: Salatiga, Jateng. Tetapi kini di sekolah kota besar yang muridnya dari kelas menengah juga ada guru yang menjauhi buku.
¬ Cuplikan infografik dari World Reading Habits in 2021 (Global English Editing)

3 Comments
Saya selalu kagum kepada orang-orang yang punya koleksi buanyak buku, dan saya asumsikan mereka pasti sudah membaca semua buku tersebut. Saya sendiri termasuk yang tidak suka membaca buku, dan karena itu sekarang hanya punya satu-dua buku di rumah, itu pun karena dikasih orang.😁 Saat saya masih kecil dan remaja saya senang membaca buku, tapi komik dan novel, dari persewaan buku.
Mengajari/membiasakan anak membaca buku? Di era internet sekarang? 🙈 Karena itu, apakah istilah kutu buku masih relevan sekarang?
1. Seperti saya bilang, saya bukan kutu buku, maka buku saya tidak banyak
2. Soal membaca buku di era digital, sekali lagi biarlah guru dan pendidik yang menjawab
🤣
😁👍🙏