
“Tentu saja pihak perpustakaan dapat menyaring buku yang diterima; jangan sampai warisan menjadi beban institusi penerima,” Hywel Coleman menulis surat pembaca di Kompas (Kamis, 22/7/2021).

Coleman menanggapi liputan Kompas 20 Juni lalu tentang buku bekas di pasar loak. Sebagian adalah buku dari perpustakaan pribadi para tokoh.

Pada banyak keluarga, soal buku akhirnya jadi masalah, terutama buku-buku tua. Jangankan para tokoh, buku warisan bapak saya saja akhirnya merepotkan ketika kami pindah ke rumah yang lebih kecil. Beberapa perabotan kami hibahkan. Buku-buku Bapak?
Nah, tak segampang mengurusi lemari dan perabot lain. Buku Bapak banyak. Sebagai poliglot, tapi tak ada anaknya yang bisa multibahasa, ada beragam buku dalam bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jawa (juga dalam aksara hanacaraka; Bapak juga bisa baca tulis Arab dan paham ilmu alam falak Arab) dan lainnya. Jumlah buku seribu lebih. Setelah Bapak meninggal, sisa buku tinggal sedikit, ada di garasi rumah Yogyakarta.
Saya tak tahu siapa saja dulu yang mendapat hibah buku sejak Bapak dan Ibu pindah ke rumah lebih kecil di Salatiga sebelum kembali ke Yogya karena sejak pindah ke rumah kecil saya sudah di Bekasi, berkeluarga. Pernah saya temukan buku Marx, juga Engels, tapi dalam bahasa Jerman. Misalnya ada versi Indonesia pun bikin mumet saya. Yang ringan ada, risalah karya Aidit, terbitan Akademi Politik Ali Archam. Bapak berprinsip, pelajarilah juga pikiran pihak yang tidak kita sukai.
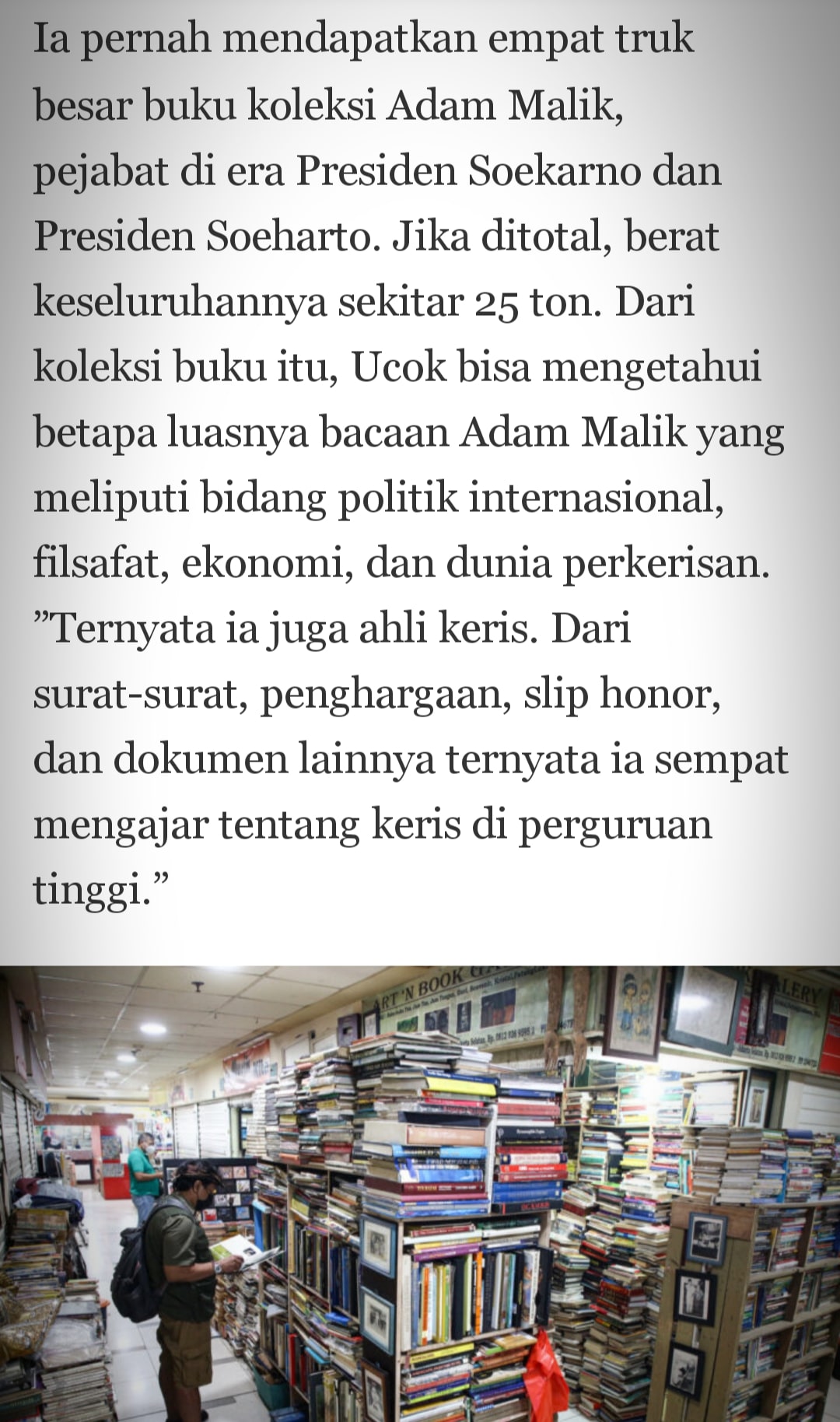
Lalu urusan semua buku dengan saya sekarang? Rumah saya kecil. Rak buku sudah tidak muat, padahal buku saya tidak banyak karena saya bukan kutu buku. Maka untuk mengurangi jumlah, tiga tahun lalu saya menghibahkan dua pertiga pustaka kepada anak kampung sebelah yang membersihkan rumah dan menata buku di rak baru saya. Dia bolak-balik mengangkut buku dan aneka barang lain dengan gerobak dorong.
Kenapa saya tak mengumumkan hibah buku kepada peminat? Tujuan saya menyingkirkan buku dengan cepat. Kalaupun buku hibah itu, banyak yang tidak penting, misalnya buku panduan komputer, bisa dijual oleh anak itu, ya bagus. Tak penting ada tanda tangan dan stempel saya daripada saya repot menyobeki halaman judul.
Menawarkan buku itu merepotkan. Peminat tidak bisa langsung datang, lagi pula dia atau mereka harus menyediakan alat angkut.
Kerepotan utama sebetulnya ini: peminat akan menyeleksi buku. Pasti menyita ruang dan waktu. Ujung-ujungnya saya yang bakal repot, harus memberesi sisanya, lalu menunggu peminat lain atau menunggu tukang loak lewat.
Moral cerita: jika setiap orang tega terhadap barang milik sendiri maka urusan cepat selesai.
Sama seperti saya dulu membuang kaset-kaset musik karena hanya merepotkan.
Saya membayangkan, tanpa yayasan yang kuat maka khazanah Fadli Zon Library — saya menduga itu perpustakaan pribadi terlengkap di Indonesia — bakal merepotkan ahli waris.
Hal sama, maaf, mungkin juga berlaku untuk perpustakaan Goenawan Mohamad dan Seno Gumira Ajidarma serta Remy Sylado.

4 Comments
Waktu saudara almarhum bapak mertua meninggal, dulu bukunya banyak yang dibawa pulang ke tanah kelahiran. Tetapi akhirnya dijual meski belum sempat memilahnya satu persatu. Rasanya seperti kehilangan harta pusaka.
Memang rasanya gimana gitu. Apa boleh buat kadang harus tega. Kalau tertunda, buku akan semakin berdebu atau berjamur tapi tak ada yang membaca. 🙏🍎
saya juga sempat mengalami kesulitan yang sama dengan koleksi komik saya saat hendak pindah ke Jerman. beberapa saya jual ke teman yang memang hobi, selebihnya ya tersimpan di rumah mertua..
Sebaiknya kita hibahkan saja. Kita akan semakin mengonsumsi konten digital.
Untuk teks, penyedia dan pengguna konten akan saling menyesuaikan.