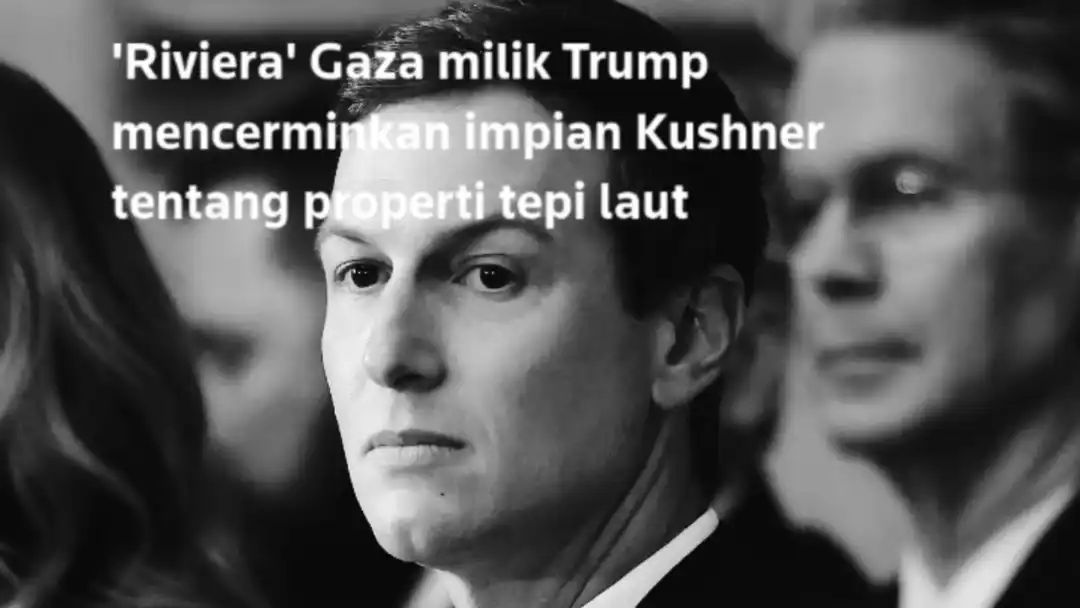Selagi saya duduk di teras , tadi diam-diam seseorang di belakang punggung saya mengintip apa yang saya baca di ponsel. Dia sedang menemani ibunya menemui istri saya.
Saya kaget, dan menyadari ada pengintip, setelah dia bersuara, “Oh, saya kira media Indonesia tapi kok tampilannya beda. Media apa itu, Oom?”
Lalu saya refresh laman yang saya baca. Sembulan opsi dari peramban Chrome untuk menerjemahkan isi ke bahasa Indonesia saya tolak. Maka tampillah Svenska Dagbladet dalam bahasa Swedia.

Lantas duduk berdiri soal pun menjadi jelas bahwa saya kerap memanfaatkan fitur penerjemahan untuk media berbahasa asing. Termasuk misalnya dari kantor berita Palestina, WAFA, dalam bahasa Arab, lalu saya baca terjemahannya.
Kadang muncul keisengan kurang praktis macam itu dalam diri saya, karena hampir semua media berita luar negeri ada versi Inggrisnya. Saya tak dapat menjelaskan kenapa kadang iseng — sekali lagi: kadang — membuka situs berita berbahasa asing non-Inggris dengan aksara bukan Latin.

“Maaf Oom, kalo baca media bahasa Inggris yang udah diterjemahin ke Indonesia, apa nggak ngurangin kemampuan bahasa Inggris kita?” tanya pria muda tamatan jurusan ilmu komunikasi yang jadi pengelola acara pengantin itu.
Saya jawab, “Gimana ya… Soalnya bahasa Inggris saya dari dulu pas-pasan, nggak bakal nambah, tapi kalo berkurang ya biarin. Saya mensyukuri teknologi. Bahwa kadang versi Indonesia kayak aneh, ya saya kira-kira aja, atau nengok versi Inggris, dengan harapan semoga paham.”

Kemudian dia permisi, “Boleh liat situs lain yang lagi Oom baca?” Saya pun membuka tab lain. Ini kebiasaan buruk saya, suka membuka jendela baru sehingga ponsel, tablet, dan komputer terbebani.
“Lho, Reuters juga bahasa Indonesia? Hahaha…” dia berkomentar. Saya tersenyum.
“Menurut Oom, apa yang layak kita kita pelajari dari gaya Reuters?”
“Kalo jadi skrinsyot bagus. Semuanya jelas. Ya judul, ya pengantar isi, lalu ada butir-butut ringkasan. Kredit foto juga jelas, itu arsip atau photo file, untuk ilustrasi berita, bukan foto dari suatu peristiwa yang diberitakan.”
“Lha itu kan biasa, Oom. Standar jurnalistik ya gitu.”
“Kalo itu standar jurnalistik, coba kamu bikin capture dari situs berita Indonesia yang populer, top of mind, liat bedanya dari Reuters. Emang sih, Reuters itu kantor berita lawas, tapi gaya ngemas berita bisa ditiru.”
Dia diam. Semoga dia sedang menimbang mana yang lebih bagus, layak skrinsyot atau layak baca utuh. Layak skrinsyot itu cuma layak di-share dan selesai, karena dari gambar tangkapan layar itu orang lain sudah tahu isi berita selintas.
Sedangkan layak baca utuh itu berupa kemasan judul dengan paragraf awal yang kurang jelas, karena pokok berita ada di bagian tengah atau akhir, dalam halaman bersambung pula untuk berlama-lama menahan pembaca, karena bounce rate adalah mimpi buruk; lebih buruk dari penulisan berita yang buruk. Tetapi, konon, berita tidak dibuat untuk jadi skrinsyot.
Siapakah yang sebenarnya kurang suka jurnalisme old skool berupa piramida terbalik dalam berita teks: para editor masa kini atau pembaca yang sebenarnya menyukai apa pun yang serbacepat?
- Slides dan peretelan info sebagai bentuk adaptasi: Hanya organisme adaptif, bukan yang terbesar dan terkuat pada masanya, yang bisa bertahan.