
Pekan lalu saya bertemu beberapa kawan, sejak sebelum makan siang hingga menjelang petang. Mereka semua senior — bukan dalam arti senang istri orang. Salah satu topik: speech delay atau telat bicara.
Ada teman saya yang cucunya, pun cucu melalui keponakannya, mengalami keterlambatan wicara, bahkan sampai usia empat tahun. Untunglah anak-anak itu segera menjalani terapi. Orangtuanya terlibat.
Maka kambing hitam sumber masalah komunikasi adalah pandemi Covid-19 dan ketergantungan anak kepada gawai elektronik. Tentang dampak Covid-19, yang mengganggu aktivitas belajar persekolahan, sila baca ringkasan laporan Bank Dunia (2022). Ada pula naskah lengkap dalam PDF. Anak-anak dari golongan ekonomi lemah lebih terdampak.
Menyangkut gawai, sebelum ada pandemi pun sudah muncul masalah. Ponsel dan tablet adalah obat untuk menghentikan kerewelan anak agar tak merepotkan orangtua. Saya pernah memotret anak bersila memegang tablet di sudut toko busana, sementara ibunya melihat-lihat baju. Sayang posting itu belum saya temukan.
Sedangkan anak-anak asyik dengan ponselnya saat diajak menghadiri kondangan, saya pernah mengeposkannya. Dalam posting itu saya mencoba becermin: “Jika anak saya masih kecil sekarang, saya tak tahu bagaimana akan menerapkan aturan berponsel“.
Soal ponsel ini memang tak terhindarkan karena banyak hal dapat, bahkan kadang harus, kita lakukan dalam ponsel pintar. Screen time berikut daftar aplikasi yang kita gunakan akan meminta penjelasan kenapa dalam sehari ada sekian jam waktu kita, sebagai orang dewasa, untuk ponsel. Terutama sebagai orangtua di depan anak berusia sepuluh tahun ke bawah. Sila buka aplikasi Digital Wellbeing.
Memang urusan ponsel dalam rumah kadang merepotkan. Tak semua keluarga dapat makan bersama di rumah tanpa ponsel di sebelas piring makan. Dalam keseharian, termasuk di dunia kerja, tak semua orang dapat membiarkan ponsel tengkurap di meja saat berbincang serius — termasuk dalam rapat. Kebiasaan imigran digital dan warga asli digital bisa sama.
Bisa saja kaum digital native sejak balita selalu melihat ayah dan ibunya, yang juga bukan imigran digital, ketika makan bersama, duduk bersama, bahkan ketika meladeni pertanyaan anak, tak lepas dari ponsel, padahal isi percakapan tak membahas gawai dan kontennya.
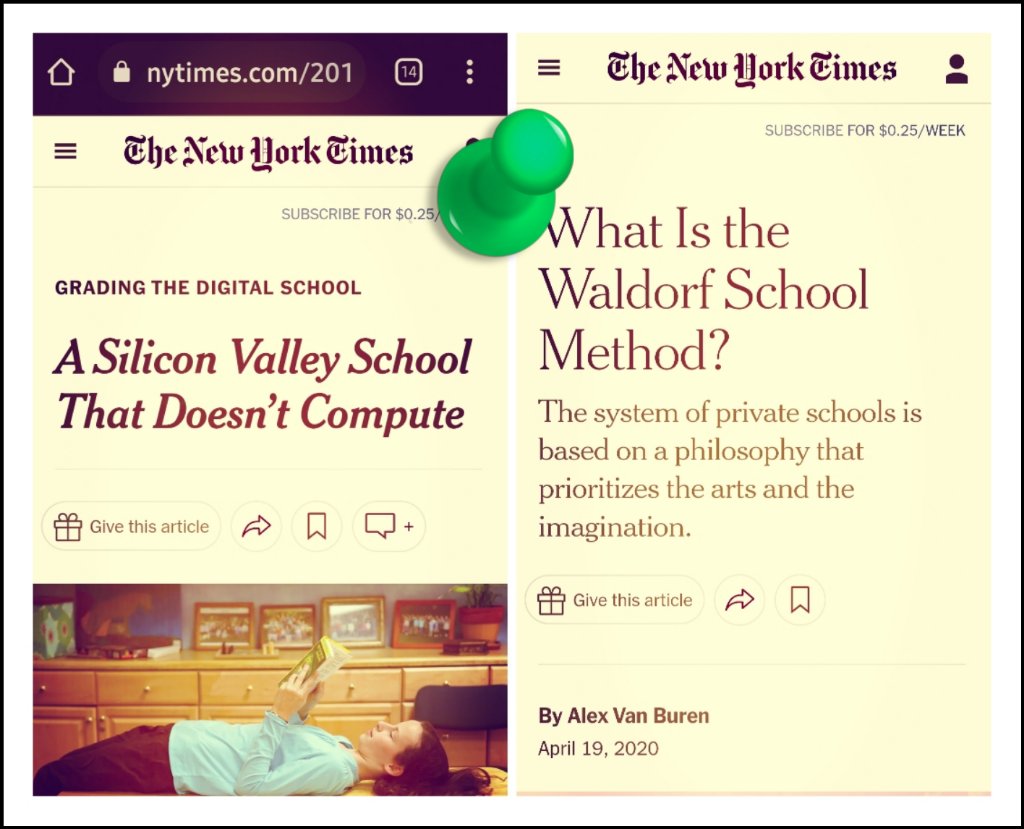
Maka dahulu, 2011, The New York Times melaporkan sekolah mahal elitis di Los Altos, California Amrik, yakni Waldorf School of The Peninsula, yang membatasi komputer, orang-orang pun terperangah. Kenapa? Orang-orang Silicon Valley menyekolahkan anaknya di sana. Saat itu saya membatin, orang-orang industri teknologi informasi telah berlaku curang.
Saya tak tahu bagaimana komputer di sekolah itu sekarang. Kondisi 2011 dan 2023 tak sama, apalagi ada pandemi, meskipun di Amrik berbeda masalah dari Indonesia.
https://youtu.be/pX4t4MgY3Zk
Laboratorium Pendidikan Dasar Sanggar Alam Anak, di Banjarnegara, ketika membahas sekolah Waldorf (2016), menutup artikel dengan pertanyaan: “Nah, masihkah Anda ngotot menjejali anak-anak dengan kemampuan penguasaan teknologi?“.
Saya tak punya jawaban. Banyak hal yang membuat saya gagap menapaki zaman.
Agar anak tak rewel di kondangan, biarkan mereka berponselria
Makan berlauk ponsel
Anggrek merpati dalam jejak peta ingatan dan speech delay
Menempatkan diri sebagai anak: “Ini adalah…”

3 Comments
Dua dari tiga cucu (dari dua anak saya), kelas satu dan kelas SD, menurut orang tua mereka, “hape teroooos.”
Mengapa cucu satunya tidak? Karena masih berusia 14 bulan.😁
Hape teroooosssss.
Apa boleh buat.
Saya kalo lagi suka baca lbh suka tablet teroooosssss sehingga gak ada WA dan telepon masoookkk
👍